Tulisan ini saya copas dari wall Andi Setiono
PERSOALAN GIBRAN TENTANG KEBOCILAN & KE-MILENEALAN-NYA
Satu2nya yang pasti hari ini, hari-hari menjelang pilpres yang sungguh menyebalkan ini. Adalah bangsa ini menemukan watak dan bentuknya yang asli: mudah nyinyir, berpikir instant, miskin rasa hormat dan duafa dalam loyalitas. Lalu apa sebabnya?
Pertama, bangsa ini adalah bangsa peniru, yang selamanya watak masyarakatnya hanya "ikut-ikutan". Bila dalam bahasa sosial media mereka disebut follower. Sayangnya, mereka adalah follower yang emosional, bukan rasional. Watak iklim tropis membuat mereka tidak butuh waktu panjang untuk memutuskan segala sesuatu. Sifat spontan, yang dahulu menjadi ciri orang pesisiran, sekarang menjadi ciri umum yang bahkan telah merasuk jauh sampai ke pedalaman. Artinya "pada bae".
Kedua, kemajuan dalam banyak hal hanya membuat masyarakatnya ternyata tak belajar apa2. Kecuali mereka adalah kelompok pengguna. Akibatnya, arah gaya hidup mereka akan menuju ke sesuatu yang semakin praktis dan instan. Sayangnya hal tersebut tidak diikuti oleh konsekuensi yang mengiringinya. Terutama dalam konteks biaya dan resiko sosialnya. Hal paling terasa dalah penggunaan smartphone dan motor dalam kehidupan sehari2. Keduanya adalah katarsis, penyeimbang untuk tetap eksis bertahan dalam kegilaan dunia nyata.
Ketiga, dan menurut saya ini yang paling parah. Orang tua adalah pihak yang paling pantas dipersalahkan dalam memilih pola asuh, pola ajar dan pola didik terhadap anak2nya. Semakin maju cara berpikir orang tua, sesungguhnya pilihannya semakin terbatas, justru karena konsekuensinya. Sedemikian membingungkannya mereka memberikan bekal untuk sang anak. Sehingga apa pun pilihannya adalah perjudian yang tak terperi hasilnya. Dunia pendidikan justru selalu menjadi titik awal keruwetan pola hubungan orang tua dan anak.
Dalam pusaran inilah kita diharuskan memahami Gibran Rakabuming Raka, yang hari2 ini secara ajaib & absurd tiba2 menjadi cawapres. Dan sebagai kalangan "old school", kita sedemikian kecewa. Karena gagal memahaminya sebagai seorang bocil sebagai wakil dari generasi mileneal.
Bila sedikit mundur, menarik ke belakang, di tahun akhir 1980-an ketika datang era globalisasi. Pada saat itu kita terkaget2 dan gagal memahaminya, bahkan jatuh paranoid karenanya. Dulu dosen saya, Pak Juwono Sudarsono berkali2 menulis di media tentang makna, sifat dan manfaat globalisasi tersebut. Sedemikian panjang lebar, karena moment yang mengiringinya adalah berakhirnya Perang Dingin dengan Amerika sebagai pemenang tunggal.
Belakangan kita menyadari bahwa globalisasi itu lebih pada Amerikanisasi. Kita harus "Menjadi Amerika" nyaris dalam segala bidang kehidupan. Kita baru menyadari bahwa terlalu banyak hal, bahkan terlau jauh sudah politik, budaya, dan gaya hidup kita yang semakin di-Amrika-kan. Walau ajaibnya, ternyata yang paling bisa mengambil manfaat dari "amerikanisasi" tersebut justru adalah bangsa China atau sebut saja Tiongkok.
Sehingga, di hari-hari ini globalisasi menemukan bentuk paling nyatanya dalam konteks Sinoisasi. Lalu apa maknanya? Yang belakangan atau dalam terminologi di atas si peniru atau follower-lah yang memetik keuntungan paling instant. Bahwa boleh saja orang lain yang menjadi penemu, tapi yang paling mengambil keuntungan adalah mereka yang bisa memproduksi, memasalkan, dan menjadikan uang. Di hari ini, mungkin lebih dari 50% produk yang ada di sekitar kita adalah merek China.
Dan begitulah kita harusnya memahami sepak terjang Gibran di hari ini, sedari awal ia muncul dan beranjak makin ke atas.
Menjelaskan kenapa ia sedemikian mudah dihina, direndahkan, dan dilecehkan. Ia sebagaimana "produk China" pada masa awal selalu dibanding2kan dengan yang lebih dulu. Ia hanya dianggap memanfaatkan posisi orang tuanya, terutama ayahnya. Ia dianggap "bocil", sesuatu yang sangat menisbikan peran dan sumbangan yang sudah ia berikan pada kotanya. Walau tetap saja sulit untuk dipungkiri kebenarannya, bahwa ia memang masih mentah dalam banyak hal. Hebatnya, ia sendiri secara terbuka, mengakui bahwa anggapan itu tidak salah dan ia bisa menerimanya.
Di titik inilah, semestinya kita memahami bahwa ia adalah pribadi yang berbeda, dari generasi yang berbeda. Ia apa yang kita sebut secara gampang sebagai mileneal, walau sesungguhnya tetap saja kita akan gagal memahaminya.
Jadi persoalannya justru terletak pada "kita-kita" yang mencoba menghakimi dengan kacamata kuda dan menelisiknya dengan pisau bedah dari generasi yang jauh lebih lampau, yang barangkali usang dan karatan. Dan lalu kita bersembunyi pada konteks2 moral dan universalitas, sesuatu yang selalu kita agung2kan tetapi sesungguhnya kita lah para pelopor pertama yang merusaknya.
Persoalan menjadi semakin lucu dan rancu, ketika kita menuntut kesetiaan dirinya pada sesuatu. Realitasnya ia bisa mudah saja berpindah usaha atau pilihan bisnis, semudah ia mengganti sendal atau t-shirt. Ia bisa saja mengganti mobilnya yang dibelinya dengan mahal, tapi menjual balik dengan murah, hanya demi mengganti isi garasinya dengan sesuatu yang dianggapnya lebih fresh. Ia adalah cerminan generasi mileneal yang tak butuh loyalitas, ia butuh ruang ekspresi yang jauh lebih personal.
Loyalitas generasi mileneal adalah pada dirinya sendiri, pada keinginan dan ambisinya sendiri.
Di titik inilah saya termasuk orang tua, yang percaya bahwa Jokowi pada mulanya pasti juga tidak merelakan anaknya bertarung di arena yang tidak benar2 ia siap hadapi, medan yang penuh binatang buas yang memang tak butuh toleransi maupun loyalitas. Gila saja, kalau Jokowi mebiarkan istrinya meluapkan dendamnya pada ibu Ketum dengan cara mengorbankan anak sulungnya yang kebetulan dari tampangnya saja memang sudah mejen, unyu, dan medioker itu.
Tapi terkadang bahkan perhitungan yang paling baik, rasional dan presisi sekalipun, bisa meleset. Menguatkan pemeo usang sepandai2 tupai melompat ia terpeleset juga. Jokowi memang berkali2 terpeleset dalam memilih "orang yang bisa dipercaya". Sesuatu yang memang nyaris mustahil di hari ini. Di titik inilah barangkali, ia pada akhirnya merelakan anaknya. Setidaknya ia masih punya istrinya, ibu dari sang anak. Yang bagaimana pun pasti akan didengar dan digugu suara dan pendapatnya.
Sialnya, lagi-lagi sialnya.
Sebagian sangat besar dari mereka-mereka yang dulu jadi pendukung Jokowi. Baik mereka yang sesungguhnya sudah memperoleh sedemikian "banyak manfaat". Mereka yang seharusnya bisa menjadi agen pencerahan, atau minimal mereka yang berkewajiban menarik tuas rem. Berhenti sejenak, menunggu, baru memberikan pendapatnya. Justru langsung nge-gas bablas, membiarkan jari jemarinya mengeluarkan kata2 yang menurut saya justru mendedah "kemiringan" watak dan karakter asli mereka.
Mereka2 yang mencoba mendayung dan berselancar masuk ke dunia mileneal, tetapi sudah gagal sejak awal di depan pintu masuk. Justru karena terlalu banyak terbebani pada "beban moral" yang sesungguhnya adalah omong kosong belaka. Mereka2 yang merasa diri "mainnya jauh", tetapi sesungguhnya tak lebih hanya menghabiskan energi tanpa anugerah kebijaksanaan baru yang seharusnya menjadi hadiah dari travelingnya itu.
Bagi saya, realitasnya Gibran, sebetapa pun terjal, berliku, dan busuk jalannya: ia telah ada di posisinya. Apa yang secara satir, ia sampaikan sebagai "saya telah ada di sini". Menjelaskan bahwa hal itu bukan melulu mau dirinya, ayahnya, maupun keluarganya. Kita yang nyinyir membacanya sebagai si bocil telah di sini. Sedang generasi yang konon 50% dari populasi NKRI itu membacanya sebagai "genrasi mileneal telah di sini".
Gak usah kaget, gak usah berteriak menuduh ini itu. Kalau Gibran dengan pasangannya itu bisa menang satu putaran!
Itu hukuman bagi kita yang telah sedemikian merendahkannya...
.
.
.
NB: Tulisan ini lahir atas permintaan dan desakan seorang ibu, orang tua tunggal, yang kebetulan anaknya besok2 ini adalah pemilih baru. Ia gusar, bingung, dan tak berdaya, bagaimana ia harus memahami anaknya yang sedemikian tergila2 pada GRR. Ia bingung dengan profiling Gibran, yang sedemikian "kaya gitu banget". Figur yang ditanya bagaimana cara mengatasi ledakan lulusan sarjana untuk memasuki dunia kerja. Dijawab ya jadi pengusaha saja. Simpel, nggampangke, dan jelas menjengkelkan.
Pribadi berwatak bocil yang ditanya sesuatu, dijawab dengan "gitu kok ditanyakan".
Namun barangkali, kita lupa bahwa ia adalah pribadi pekerja keras ala2 generasi mileneal. Generasi yang mewarisi beban harus berbuat sesuatu yang baru, tapi sekaligus musti dengan cepat dan biaya murah. Ia adalah generasi yang meyakini korupsi adalah sejelek2nya tabiat bangsa ini, yang paling sulit disembuhkan. Ia yang barangkali telah jengah dengan gaya berdebat kusir, tapi sesungguhnya nyaris tidak bisa bekerja secara kongkret.
Gibran adalah generasi yang lain, dimana yang kita iri dan dengki-kan adalah fasilitas yang dimiliki dan diberikan bapaknya. Sambil kita lupa, ia berani mengambil resiko dan menanggung beban yang seharusnya masih ada di pundak bapaknya. Jelas ia berani mengambil resiko untuk disalah pahami dan dalam konteks tertentu memperpanjang nafas majalah Tempo untuk menjadikannya bahan caci maki dengan berbagai media reportasenya. Weih.
Saya hanya mencoba sedikit membuat imbang, jika di lingkaran pertemenan saya semua menjadi public-enemy bagi Gibran. Setidaknya saya melihatnya sebagai bocil yang berani dan beruntung, yang pandai memanfaatkan ke-milenal-annya. Sesuatu yang di generasi sebelumnya, sekalipun berusaha keras memahaminya, tetap saja selalu berakhir gagal.
Karena apa? Karena ke-milenal-an memang bukan miliknya...




:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4684007/original/023535800_1702399692-20231212-Momen_Akhir_Debat_Perdana-FAI_9.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4684000/original/003651800_1702399688-20231212-Momen_Akhir_Debat_Perdana-FAI_2.jpg)




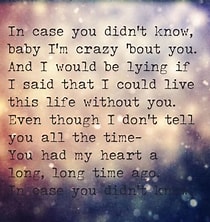

.JPG)



.JPG)

.JPG)








.JPG)


.JPG)











